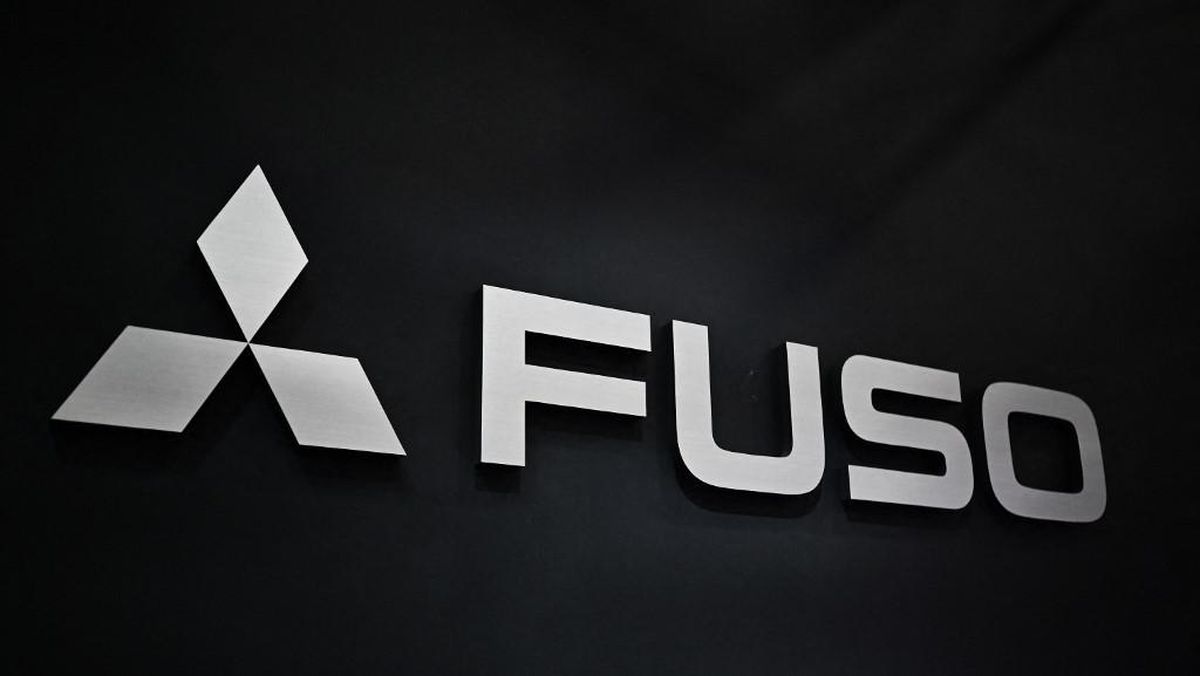Jakarta, CNN Indonesia --
Laporan World Economic Forum (WEF) menempatkan Pakistan sebagai salah satu negara di dunia yang berbahaya bagi perempuan.
Dalam laporan Global Gender Gap Report 2025 oleh WEF, Pakistan berada di peringkat ke-148 dengan skor paritas keseluruhan turun dari 57,7% menjadi 56,7%. Penurunan ini menandai kemunduran dua tahun berturut-turut.
Partisipasi ekonomi perempuan di Pakistan terus merosot, sementara kesetaraan literasi masih di bawah 75 persen. Data tersebut mencerminkan ketimpangan struktural yang dalam dan budaya patriarki yang mengakar di sana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam masyarakat yang diatur oleh norma patriarki, kekerasan berbasis gender tetap menjadi bagian rutin kehidupan. Patriarki berfungsi sebagai sistem sosial yang membatasi otonomi perempuan dan memperkuat dominasi laki-laki, baik dalam institusi formal maupun interaksi sehari-hari.
Kehormatan keluarga kerap dikaitkan dengan kesucian perempuan, dan praktik adat yang merugikan sering dibungkus pembenaran agama atau budaya.
Praktik berbahaya seperti pembunuhan demi kehormatan (honour killings), pemerkosaan, pelecehan seksual, serangan asam, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan paksa, dan kekerasan dalam tahanan terus berlangsung.
Kekerasan ini tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga tertanam dalam institusi formal, ditegakkan dewan suku (jirga), dan kerap ditoleransi negara.
Dewan suku
Aurat March, aksi tahunan yang menuntut keadilan gender, pada Maret 2025 mendesak pemerintah menetapkan kekerasan berbasis gender sebagai darurat nasional. Namun seruan itu tidak mendapat tanggapan resmi.
Kasus Asma Jattak dari Balochistan menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan perempuan. Pada 5 Februari 2025, Asma diculik oleh Zahoor Jamalzai, pria dengan koneksi politik dan suku yang kuat. Zahoor diduga membunuh tunangan Asma pada 2012 dan selama bertahun-tahun menekan keluarganya untuk menikahkan Asma. Meskipun desakan publik berhasil membebaskannya, Zahoor tetap bebas karena dilindungi hubungan dengan para sardar berpengaruh.
Peran jirga atau dewan suku dalam melanggengkan kekerasan juga menjadi sorotan. Mereka kerap mengeluarkan hukuman di luar hukum, termasuk pemerkosaan massal, pernikahan paksa melalui vani atau swara, dan pembunuhan demi kehormatan. Pada Juli 2025, Bano Bibi dan Ihsan Ullah dieksekusi oleh jirga di Balochistan karena diduga menjalin hubungan di luar nikah.
Kata-kata terakhir Bano, "Mari, berjalan tujuh langkah denganku lalu kau bisa menembakku," terekam video dan beredar luas, memicu kemarahan publik. Namun, di media sosial seperti TikTok, muncul pula konten berbasis AI yang justru memuliakan pelaku atas nama kehormatan.
Sekitar 1.000 perempuan dibunuh setiap tahun di Pakistan atas nama kehormatan, dengan 405 kasus tercatat resmi pada 2024.
Aktivis hak perempuan Fatima Khilji mencatat bahwa loyalitas suku kerap memaksa keluarga membenarkan pembunuhan ini. Dalam kasus Bano, ibunya merilis video yang membela sistem suku dan menjelekkan putrinya sendiri, diyakini akibat tekanan para tetua.
Kekerasan semacam ini juga marak di kota besar. Di Quetta, seorang ayah baru-baru ini membunuh putri dan keponakannya karena menolak perjodohan. Awal tahun ini, seorang ayah lain membunuh putri berusia 15 tahun yang lahir di AS karena memposting video di TikTok.
Lingkaran kekerasan
Ruang digital yang sebelumnya dianggap sarana pemberdayaan kini menjadi medan pelecehan.Pada Juni 2025, bintang TikTok 17 tahun Sana Yousaf ditembak mati oleh pria yang berulang kali menghubunginya secara daring.
Menurut Digital Rights Foundation, 58,5% laporan pelecehan online di Pakistan diajukan oleh perempuan. Internet yang seharusnya memberi kebebasan sering justru menjadi saluran ancaman, pelanggaran privasi, dan kekerasan di dunia nyata.
Kekerasan dalam rumah tangga tetap merajalela. Survei menunjukkan 34% perempuan mengalami kekerasan dari suami, namun drama televisi Pakistan kerap meromantisasi kekerasan ini dengan narasi kehormatan dan kepatuhan, memperkuat norma patriarki dan menumpulkan kepekaan publik.
Krisis kekerasan berbasis gender di Pakistan menunjukkan kegagalan negara dan masyarakat dalam melindungi perempuan. Keengganan pemerintah menghadapi jirga, tingkat vonis pengadilan yang sangat rendah (0,1% dalam kasus penculikan), dan normalisasi kekerasan di media memperkuat budaya impunitas. Hukum internasional dan perjanjian hak asasi menjadi tidak berarti ketika negara memilih diam.
Para aktivis menilai bahwa untuk membongkar sistem patriarki, langkah hukuman saja tidak cukup. Dibutuhkan perubahan budaya yang menolak glorifikasi kekerasan, menempatkan pengalaman penyintas sebagai pusat perhatian, serta menegaskan otonomi dan martabat perempuan sebagai pemilik hak dan suara.
(dna)