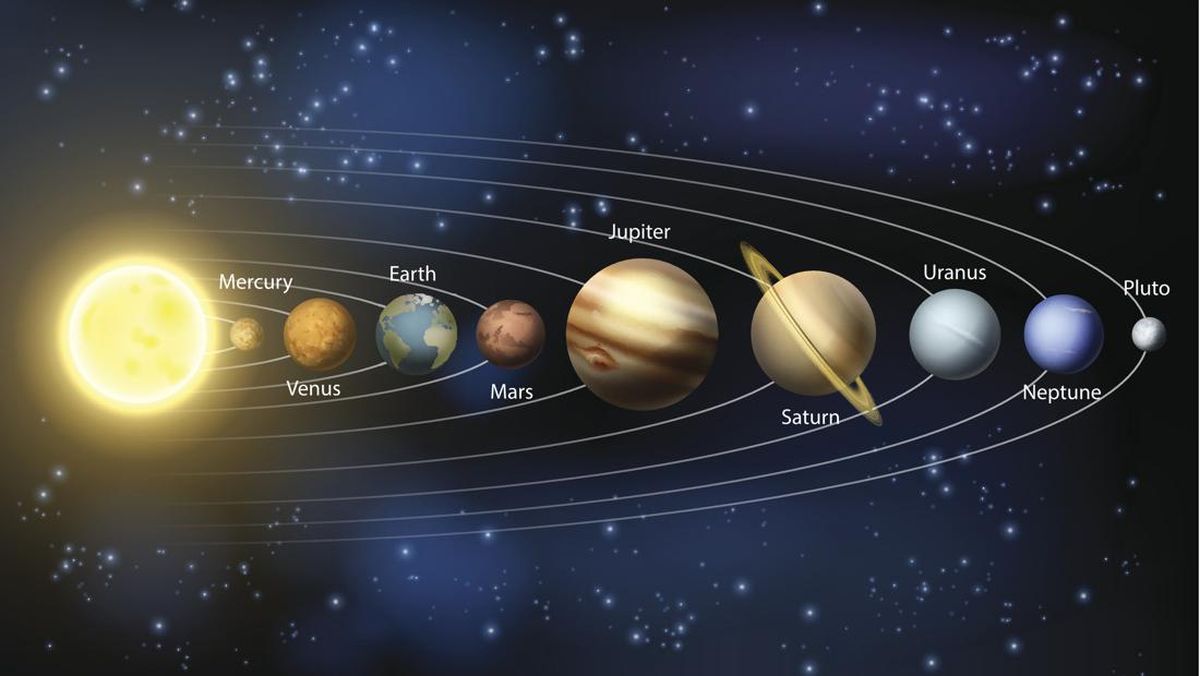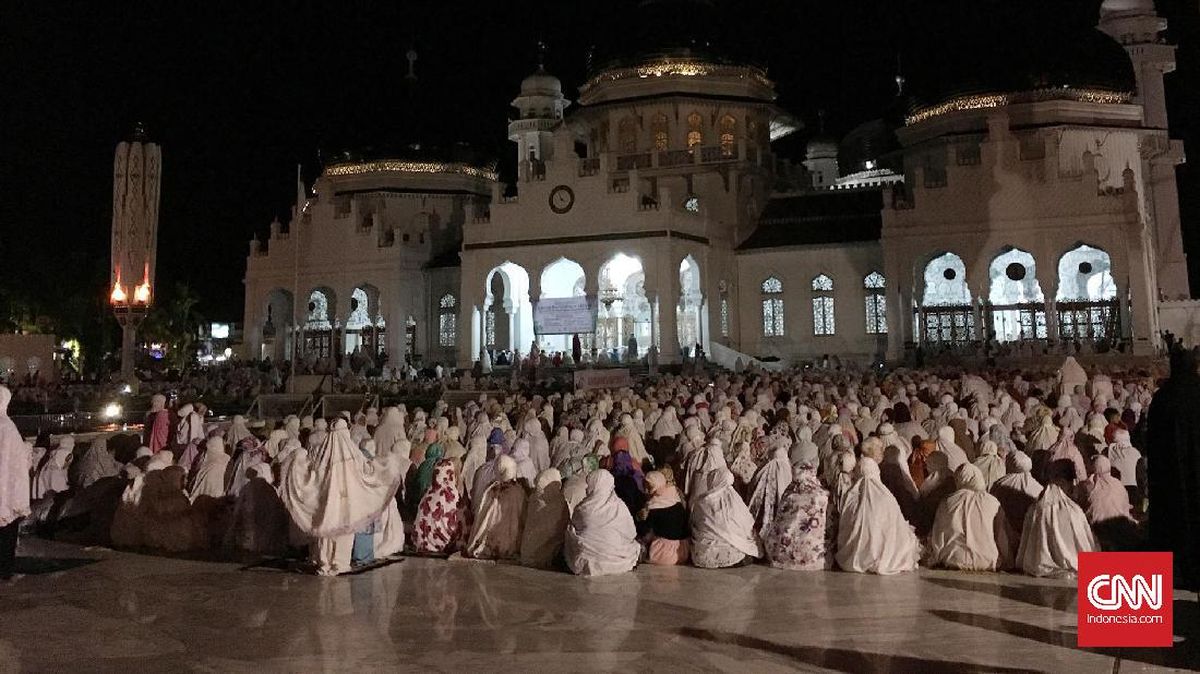Jakarta, CNN Indonesia --
Kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini terus terjadi, mulai dari kekerasan seksual yang dilakukan mantan Guru Besar Fakultas Farmasi UGM terhadap belasan mahasiswanya. Teranyar kekerasan seksual juga mencuat, yang dilakukan Dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung terhadap pendamping pasien.
Dalam kasus kekerasan seksual korban kerap kali tidak memiliki kemampuan melawan. Reaksi ini bukan berarti korban pasrah dengan apa yang mereka alami, hal ini justru merupakan respons tubuh yang dikenal dengan istilah tonic immobility.
Apa itu tonic immobility?
Melansir MCASA, Tonic immobility adalah bentuk reaksi bawah sadar tubuh terhadap ancaman, terutama ketika otak menilai bahwa melawan atau melarikan diri akan memperbesar risiko bahaya. Kondisi ini telah lama diamati pada hewan, seperti possum yang berpura-pura mati saat didekati predator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, riset menunjukkan bahwa tonic immobility juga terjadi pada manusia, terutama dalam kasus kekerasan seksual.
Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 70 persen dari hampir 300 perempuan yang menjadi korban pemerkosaan melaporkan telah mengalami gejala tonic immobility. Sebanyak 48 persen di antaranya mengalami gejala ekstrem, seperti tubuh yang sepenuhnya kaku, tak bisa bersuara, dan merasa mati rasa sepanjang kejadian.
"Tonic immobility bukan bentuk persetujuan, bukan pula tanda kelemahan. Itu adalah reaksi otak terhadap ketakutan ekstrem. Sama sekali di luar kendali korban," kata Dokter Jim Hopper, pakar trauma dari Harvard Medical School menukil Scientific American.
Riset menunjukkan bahwa korban yang mengalami tonic immobility memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) dan depresi berat. Banyak dari mereka menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa melawan atau berteriak, terutama di tengah tekanan sosial yang menuntut korban untuk bereaksi.
"Rasa bersalah dan malu ini menjadi hambatan besar dalam proses penyembuhan korban," ujar Anna Möller, ginekolog dari Karolinska Institute dan penulis utama studi tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemahaman tentang tonic immobility dapat membantu korban mengurangi rasa bersalah dan memahami bahwa mereka tidak memilih untuk membeku tapi tubuh mereka yang memutuskan.
Penelitian ini juga diperkuat oleh temuan dari Harvard Review of Psychiatry yang menyebutkan bahwa tonic immobility adalah bagian dari 'defense cascade' dalam sistem saraf manusia. Ketika melawan atau kabur tidak memungkinkan, tubuh memilih 'membeku', lumpuh total demi mengurangi rasa sakit dan memperbesar kemungkinan selamat.
Kebanyakan dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa ketika diserang, kita akan melawan atau kabur-fight or flight. Tapi sebelum dua reaksi itu, otak secara otomatis masuk ke mode "freeze", menilai bahaya yang datang.
Ketika otak memutuskan bahwa melawan akan sia-sia atau berisiko lebih besar, tubuh akan "mematikan" dirinya sendiri melalui tonic immobility. Ini bukan bentuk kepasrahan, apalagi tanda "mengizinkan", melainkan reaksi naluriah demi bertahan hidup.
Akibatnya, banyak korban justru merasa bersalah. Mereka menyalahkan diri sendiri karena tak bisa melawan, merasa malu karena membeku, atau takut tak dipercaya karena diam. Padahal, mereka hanya mengikuti instruksi otak yang sedang panik dan mencoba menyelamatkan mereka.
(tis/tis)